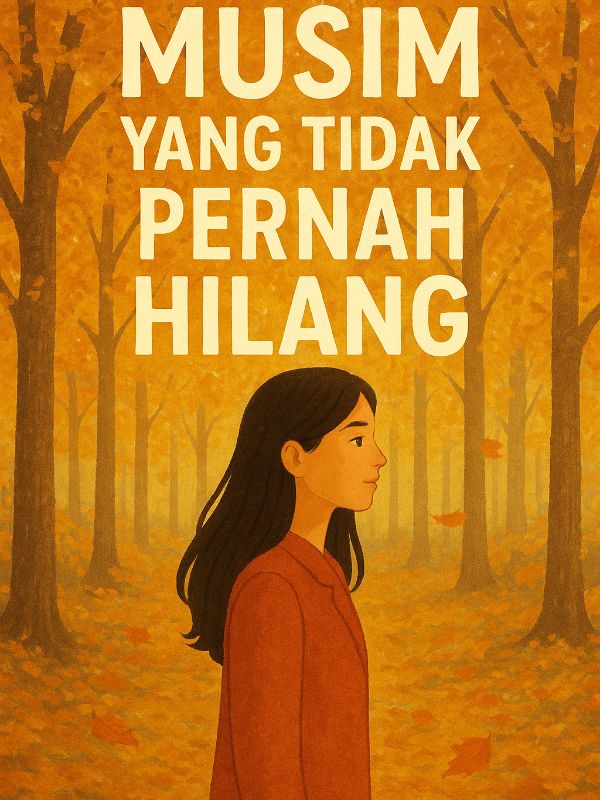
Musim yang Tidak Pernah Hilang
Angin sore berhembus pelan melewati pepohonan jati yang tumbuh sepanjang jalan desa Wana Sari. Awan tipis melayang perlahan di atas langit jingga, membentuk pola-pola indah yang disukai Reno, seorang remaja kelas X yang gemar menggambar. Ia duduk di bale-bale bambu depan rumahnya sambil memandangi langit yang berubah warna.
Reno menggoreskan pensil di buku gambarnya, menggambar burung camar yang terbang di antara awan. Ia sering merasa lebih bebas ketika menyentuh kertas—sesuatu yang membantunya menghadapi hari-hari sulit di rumah. Ibunya bekerja sebagai penjual sayur keliling, sementara ayahnya merantau ke luar pulau dan jarang pulang.
Saat Reno sedang asyik menggambar, suara langkah kaki mendekat cepat.
“Renooo! Aku bawa berita penting!”
Itu Mira, sahabat sekaligus tetangganya. Rambut sebahunya diikat karet hijau, dan ia tampak bersemangat seperti biasa.
“Ada apa lagi?” Reno tersenyum tipis.
“Sekolah bikin lomba karya seni tingkat kecamatan! Dan hadiahnya beasiswa satu semester!” teriak Mira sambil menunjuk kertas pengumuman di tangannya.
Reno mengangkat alis. “Beasiswa? Serius?”
Mira mengangguk cepat. “Kamu harus ikut. Kamu jago gambar!”
Reno menatap bukunya, lalu menutupnya perlahan. “Aku nggak yakin. Pesertanya pasti banyak.”
“Justru itu,” Mira mendekat dan menepuk pundaknya. “Yang banyak itu kesempatan. Kamu cuma perlu ambil salah satunya.”
Reno tertawa kecil. “Terdengar puitis banget. Kamu belajar dari siapa?”
“Dari poster motivasi di kelas Bu Tika,” jawab Mira sambil menepuk dada bangga.
Reno terdiam sejenak. Beasiswa itu bukan hanya tentang kebanggaan. Ia tahu ibunya sering menahan keinginan membeli uang jajan ekstra atau perlengkapan gambar yang ia butuhkan. Kadang Reno merasa bersalah.
Mira menuntun Reno bangkit dari bale. “Kamu ikut ya? Aku udah lapor Bu Tika kalau kamu tertarik.”
“Astaga, Mir—”
“Kamu nggak boleh mundur!”
Reno akhirnya menghela napas dan tersenyum. “Oke, aku ikut.”
Mira bersorak seperti anak kecil. “YES!”
---
Malam itu, setelah makan, Reno duduk di meja belajar kecilnya. Lampu redup menyoroti kertas kosong yang belum tersentuh. Tema lomba itu adalah “Musim yang Tak Terlupakan.”
Reno mengetuk-ngetuk pensil di meja. Musim apa yang tidak terlupakan baginya?
Ada musim hujan ketika ayah belum pulang selama dua tahun. Ada musim kemarau ketika ibunya jatuh sakit dan Reno harus membantu berjualan sayur. Ada juga musim di mana ia menemukan kegemaran menggambar, saat ia berusia delapan tahun.
Tapi ada satu musim yang lebih kuat dari semuanya—musim saat ayah pergi merantau dan berkata, “Ayah nggak lama kok.” Padahal kenyataannya, ayah jarang sekali memberi kabar.
Reno menghela napas. “Musim yang tidak pernah hilang…”
Ia mulai menggambar siluet seorang anak kecil yang berdiri di tepi ladang, memandangi jalan panjang yang mengarah keluar desa. Langit dalam gambar itu penuh warna, namun di sudutnya ada awan gelap—simbol perasaan yang tak terucap.
Tangannya terus bergerak, semakin cepat, semakin mantap.
Waktu berlalu tanpa ia sadari.
Saat ia berhenti, jam sudah menunjukkan pukul 23.15. Reno menatap hasilnya dan merasa lega. Ada emosi yang mengalir di setiap goresan.
Ia berbisik pelan, “Semoga ini cukup…”
---
Pagi berikutnya, Reno menyerahkan karyanya pada Bu Tika. Guru seni itu menatap hasil gambarnya lama, lalu tersenyum puas.
“Ini kuat sekali, Reno,” katanya. “Bukan hanya gambar, tapi cerita.”
Pipi Reno memerah. “Terima kasih, Bu.”
Mira yang berdiri di sampingnya ikut berkomentar. “Bu Tika, Reno itu memang jago dari dulu. Tapi dia suka terlalu rendah hati.”
Reno menyikut Mira. “Hush!”
Bu Tika tertawa. “Kalian memang tidak pernah berubah.”
Dua minggu berlalu. Pengumuman pemenang lomba akan dipasang di balai kecamatan setelah acara pameran seni kecil-kecilan. Mira memaksa Reno datang, walau Reno sebenarnya gugup setengah mati.
Ketika mereka tiba, puluhan warga sudah berkumpul. Sepanjang dinding balai, karya seni peserta dipajang rapi. Reno melihat gambarnya dipasang di bagian tengah—posisi yang cukup mencolok.
“Lihat, Ren. Gambarmu banyak yang nonton,” bisik Mira sambil tersenyum lebar.
Reno menelan ludah. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian seperti ini.
Tak lama kemudian, panitia naik ke panggung kecil dan mengambil mikrofon.
“Baik, kami akan mengumumkan tiga karya terbaik.”
Jantung Reno berdegup cepat.
“Juara tiga… Nomor peserta 07.”
Bukan Reno.
“Juara dua… Nomor peserta 12.”
Masih bukan Reno.
Mira menggenggam tangan Reno. “Tenang… kalau bukan tiga besar pun nggak apa-apa…”
Pengumuman terakhir pun tiba.
“Dan juara pertama lomba karya seni kecamatan tahun ini adalah… Nomor peserta 09.”
Reno terpaku.
Tapi seluruh ruangan menoleh ke arahnya.
Mira memekik, “RENO! NOMOR KAMU 09! YA AMPUN KAMU JUARA SATU!”
Tepuk tangan meletup seperti ledakan kecil. Bu Tika melangkah maju dengan wajah bangga, mendorong Reno ke depan.
Reno berjalan dengan langkah kaku, seolah mimpi. Ketika menerima sertifikat dan piala kecil, matanya berkaca-kaca.
Ini pertama kalinya sesuatu dalam hidupnya terasa… benar-benar membuahkan hasil.
Sepulang dari acara itu, Reno menemani ibunya berjualan sayur ke desa sebelah. Ibunya tampak sangat bahagia mengetahui Reno menang.
“Kamu itu memang pintar menggambar dari kecil,” kata ibunya sambil mengayuh sepeda sayur. “Ayahmu selalu bilang begitu.”
Nama itu membuat Reno terdiam. Sudah lama ia tidak mendengar kabar ayah.
Ibu melanjutkan, “Kalau ayahmu lihat kamu sekarang, dia pasti bangga.”
Reno tidak menjawab. Ada rasa hangat bercampur getir di dadanya. Kemenangan lomba itu memperkuat satu hal: ia merindukan ayahnya.
Beberapa hari kemudian, ketika Reno sedang menggambar di bale depan rumah, seorang pria muncul di ujung jalan desa, membawa tas besar.
Reno mengerutkan dahi. Sosok itu tampak familiar—dongak, rambut acak, kulit yang menggelap karena kerja di luar ruangan.
“Ayah?” suara Reno tercekat.
Pria itu tersenyum lemah. “Reno….”
Reno berdiri. Dunia seakan berhenti berputar.
Ayah berjalan mendekat dengan mata yang ikut berkaca.
“Ayah pulang.”
Reno menggigit bibir bawahnya, menahan segala emosi yang menumpuk bertahun-tahun.
“Ayah… lama sekali.”
Ayah menunduk. “Ayah minta maaf.”
Reno tidak tahu harus merespon apa. Sebagian dirinya marah. Namun bagian lain hanya… rindu.
Tanpa sadar, Reno melangkah maju dan memeluk ayahnya.
Ayah membalas pelukan itu erat. “Maafkan Ayah, Ren. Ayah janji nggak akan pergi lama lagi.”
Air mata turun di pipi Reno. Bukan air mata kesedihan. Tapi pelepasan.
---
Hari-hari berikutnya, keluarga kecil itu kembali terbentuk pelan-pelan. Ayah membantu ibu berdagang. Ia juga memperbaiki bagian rumah yang rusak, memasak makanan favorit Reno, dan sering duduk menemani Reno menggambar.
Reno merasa lebih ringan—seperti ada beban besar yang akhirnya dilepaskan.
Namun ia masih belum tahu apa langkah hidupnya selanjutnya.
Suatu sore, saat menggambar di bale-bale, ayah berkata, “Ren, kamu pernah kepikiran buat masuk sekolah seni?”
Reno kaget. “Sekolah seni?”
“Iya. Bakatmu besar. Sayang kalau nggak dikembangkan.”
Reno menggenggam pensilnya. “Tapi sekolah seni mahal, Yah.”
Ayah tertawa kecil. “Kalau kamu bisa menang lomba kecamatan, kamu bisa menang lomba yang lebih besar. Beasiswa itu ada buat anak-anak seperti kamu.”
Reno menatap ayah. “Ayah yakin?”
“Ayah sangat yakin.”
Kata-kata ayah itu seperti bensin bagi api kecil dalam diri Reno.
Beberapa minggu kemudian, datang undangan dari panitia kabupaten: pemenang lomba kecamatan diundang mengikuti pameran tingkat kabupaten, sekaligus seleksi beasiswa seni untuk tingkat provinsi.
Reno menunjukkan surat itu pada ayah dan ibu. Mereka hanya tersenyum bangga.
Namun Reno tetap gugup.
Mira datang sore itu dan menemukan Reno duduk menatap surat tanpa ekspresi.
“Halo, Picasso lokal.” Mira menepuk punggungnya. “Kamu kenapa?”
“Aku takut… gagal,” jawab Reno pelan.
Mira langsung duduk bersila di depan Reno. “Reno. Kamu sudah melalui banyak hal. Kamu berhasil melampaui rasa takutmu waktu ikut lomba kecamatan. Kamu bahkan bisa menghadapi perasaanmu tentang ayahmu. Sekarang kamu takut lagi?”
Reno menunduk.
Mira menghela napas. “Takut itu normal. Tapi jangan biarin takut mengatur hidupmu. Kamu itu kuat. Kamu cuma perlu yakin sama diri sendiri.”
Reno menatap Mira. “Kalau aku gagal gimana?”
Mira tersenyum lembut. “Kalau kamu gagal, kamu masih Reno. Reno yang berusaha. Reno yang tetap punya mimpi. Dan aku bakal tetap di sini buat bantu kamu.”
Perkataannya membuat Reno tersenyum. Mira memang selalu bisa menemukan cara yang tepat untuk menyemangatinya.
Hari pameran di kabupaten pun tiba.
Reno berangkat bersama orang tuanya. Kali ini, ia tidak pergi dengan rasa kosong seperti dulu. Ada keluarga yang mendukungnya. Ada sahabat yang percaya padanya. Dan ada mimpi yang mulai berbentuk jelas.
Di aula besar tempat pameran berlangsung, karya-karya seni dari berbagai kecamatan terpajang. Reno berdiri di depan karyanya—gambar baru yang ia buat: seorang anak duduk di antara pepohonan jati, menggambar langit. Di belakang anak itu, terlihat bayangan kedua orang tuanya.
Judulnya: “Musim yang Tidak Pernah Hilang.”
Ketika juri mendekat, Reno menceritakan makna karyanya dengan penuh keyakinan. Ia berbicara tentang kehilangan, kerinduan, perbaikan diri, dan musim-musim dalam hidup yang membentuk seseorang.
Juri mendengarkan dengan seksama.
Setelah satu jam, pengumuman dilakukan.
“Pemenang beasiswa seni provinsi tahun ini adalah…”
Reno menggenggam tangan ayah dan ibunya.
“… Reno Adikara dari Desa Wana Sari!”
Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan. Ibu menangis bahagia, ayah menepuk bahu Reno dengan bangga. Reno tidak dapat menahan air matanya.
Ia menangis sambil tersenyum.
Bukan hanya karena menang.
Tapi karena akhirnya ia merasa… ia berada di jalan yang seharusnya.
Dalam perjalanan pulang, ayah berkata, “Ini baru awal, Ren. Musim hidupmu baru mulai.”
Reno melihat jendela mobil, memandangi langit senja yang perlahan berubah warna.
Ia menggenggam buku gambarnya erat-erat.
“Ya, Yah. Ini baru awal.”
Dan dari hari itu, Reno berjanji pada dirinya sendiri:
Tidak peduli musim apa pun yang akan datang, ia akan tetap melangkah.
Sebab musim yang tidak pernah hilang adalah harapan—dan harapan itu kini tumbuh di dalam dirinya.
Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin lembut mengelus wajahnya, dan merasakan keyakinan itu tumbuh sedikit demi sedikit. Jalan di depan masih panjang, tanjakan mungkin menunggu, tapi hatinya mantap melangkah, melanjutkan kisah yang baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Reno merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian dalam hidup yang sering kali mengejutkan ini, seolah seluruh dunia perlahan menuntunnya ke arah yang tepat penuh ketenangan.