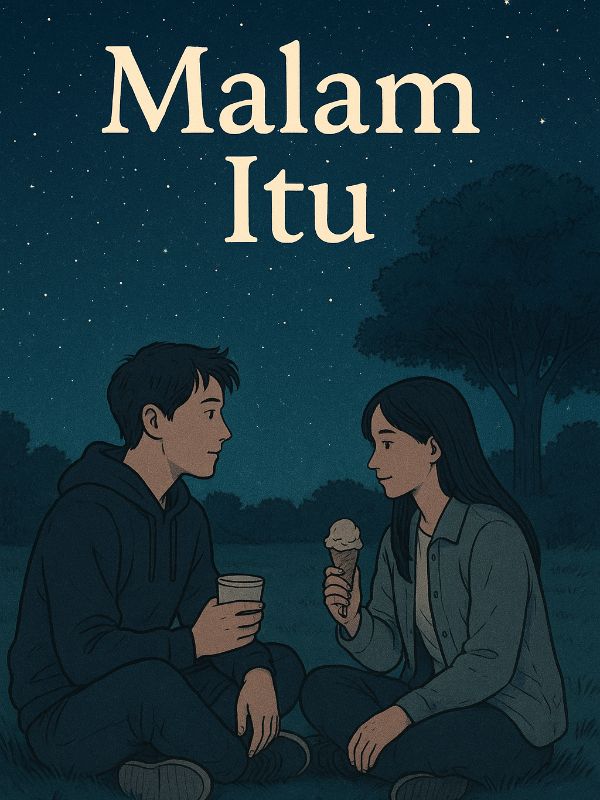
Langit di Atas Lapangan Sekolah
Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah percakapan mereka berhenti di antara desir angin dan sendok es krim yang mulai mencair, Rafi dan Aira tetap duduk tanpa perlu berkata apa-apa lagi. Keheningan itu bukan canggung—lebih seperti jeda panjang yang nyaman, seolah lapangan, pohon angsana, dan suara jangkrik sedang memberi mereka kesempatan untuk bernapas.
“Hari ini… seru, ya,” kata Aira akhirnya. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara sepatu futsal di kejauhan dari anak-anak kelas lain yang baru selesai latihan.
“Seru,” jawab Rafi. “Capek, tapi seru.”
Aira tersenyum sambil menggambar garis-garis kecil di cup es krimnya yang sudah kosong. “Kamu tadi keren banget. Serius, Raf. Aku kira kamu bakal jatuh waktu dribble yang terakhir itu.”
“Kamu kira aku selemah itu?” goda Rafi.
“Bukan. Aku cuma tahu kamu suka gugup kalau diperhatiin,” balas Aira cepat.
Rafi menghela napas pendek. “Kalau yang perhatiin kamu, ya… wajar gugup.”
Aira memalingkan wajah, seolah menatap sesuatu jauh di tengah lapangan. “Kamu tuh, ya,” gumamnya, tapi nada suaranya tidak marah.
Mereka kembali diam. Kali ini keheningannya berbeda—lebih hangat, lebih berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara menunggu untuk dijatuhkan. Tapi kedua remaja itu masih menahan, seolah takut jika salah satu dari mereka mencoba menyentuh kata-kata itu, semuanya akan pecah.
Setelah beberapa menit, Aira berdiri sambil menepuk celananya. “Aku pulang dulu, ya? Besok ada kuis matematika. Aku kalau nggak belajar, bisa kacau.”
Rafi berdiri juga. “Mau aku anter?”
Aira menggeleng. “Nggak usah. Rumahku deket kok. Lagian kamu pasti mau ngelamun dulu.”
“Ketahuan,” kata Rafi sambil tersenyum kecil.
Aira melangkah beberapa meter sebelum berhenti dan menoleh. “Raf.”
“Hm?”
“Jangan terlalu mikirin hal-hal yang nggak kamu punya. Kadang yang kamu punya itu… udah cukup.”
Rafi ingin bertanya maksudnya. Tapi Aira sudah melambaikan tangan dan berjalan pergi, meninggalkannya di bawah lampu taman yang temaram.
Keesokan harinya, suasana sekolah jauh lebih ramai dari biasanya. Kemenangan tim sepak bola, meski hanya mendapatkan perak, tetap saja membuat banyak siswa bangga. Poster-poster ucapan selamat ditempel di mading, dan nama Rafi berulang kali disebut sepanjang koridor.
Saat jam istirahat, Rafi membuka loker dengan lesu. Teman-temannya menggodanya tanpa henti sejak pagi. Semuanya tentang gol dramatis itu… atau tentang Aira.
“Bro, kamu sama Aira jadian nggak sih?” tanya Dimas, teman satu timnya.
“Enggak,” jawab Rafi cepat.
“Tapi kemarin aku lihat kalian makan es krim berdua di lapangan,” tambah Bagas sambil menyikut lengan Rafi.
“Itu cuma—”
“Sahabat, ya ya ya,” potong Dimas. “Klasik banget.”
Rafi hanya menutup pintu loker dan berjalan pergi, mengabaikan tawa mereka. Ia tahu teman-temannya tidak salah—ada sesuatu antara dirinya dan Aira. Tapi sesuatu itu seperti awan tipis yang selalu berubah bentuk. Tidak bisa ia genggam, tapi selalu ada di sana.
Di ujung koridor, ia melihat Aira sedang berjalan sambil memeluk buku. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia mempercepat langkah, tapi tiba-tiba Kevin muncul dari arah berlawanan dan menghampiri Aira.
Jantung Rafi langsung jatuh.
Kevin dan Aira berbicara sebentar. Kevin tertawa kecil, lalu menepuk bahu Aira dengan santai sebelum pergi. Aira hanya tersenyum tipis, tetapi itu cukup untuk membuat perut Rafi seperti diremas.
Saat Aira melihatnya, ia melambaikan tangan. “Raf!”
Rafi berjalan mendekat. “Pagi,” katanya singkat.
Aira mengamati wajahnya selama beberapa detik. “Kamu kenapa?”
“Enggak apa-apa.”
“Aku kenal kamu,” kata Aira sambil mengerucutkan bibir. “Pasti ada apa-apa.”
Rafi menggigit bibir. “Barusan sama Kevin ya?”
Aira mengangguk. “Dia cuma bilang selamat buat pertandingan kemarin. Terus nanya soal latihan tim basket minggu depan. Santai aja.”
Rafi mengangguk. Tapi hatinya tidak santai sama sekali.
Aira menatapnya lebih lama. “Raf… kamu nggak perlu khawatir sama Kevin. Beneran.”
“Aku nggak khawatir,” bantah Rafi.
“Ya ampun. Kamu selalu gitu kalau bohong,” kata Aira sambil tertawa kecil.
Rafi menunduk. “Aku cuma… nggak tahu posisi aku sekarang.”
Aira terdiam. “Raf”
Bl sekolah berbunyi, dan percakapan itu terputus tanpa kejelasan.
Malam harinya, Rafi kembali ke lapangan. Kebiasaan lama yang tidak pernah gagal membuat kepalanya sedikit lebih tenang. Ia menendang bola perlahan, membiarkan suara pantulan dan gesekan sepatu menjadi ritme yang menenangkan.
“Latihan sendiri lagi?”
Rfi menoleh. Aira berdiri di pinggir lapangan dengan jaket abu-abu dan dua gelas minuman hangat.
“Kamu kok di sini?” tanya Rafi.
“Aku cuma mikir… kayaknya kamu butuh ditemenin.”
Aira menyerahkan salah satu gelas. Cokelat panas. Kesukaan Rafi sejak dulu.
“Kamu beneran nggak apa-apa soal Kevin?” tanya Aira langsung. Kali ini nadanya serius, tanpa tawa atau godaan.
Rafi menghela napas panjang. “Aku cuma takut. Takut kalau kamu milih dia terus aku… hilang.”
Aira mendekat satu langkah. “Raf, aku nggak pergi ke mana-mana.”
“Tapi kamu juga bilang kamu takut kalau kita berubah.”
Aira menunduk, menggenggam gelasnya erat-erat. “Iya. Aku takut banget. Soalnya kamu itu… penting. Terlalu penting.”
Rafi menatap langit sama seperti malam sebelumnya. “Terus kita harus gimana?”
Aira diam lama sebelum menjawab. “Kita… pelan-pelan aja. Nggak harus langsung berubah. Tapi juga nggak perlu pura-pura nggak ada apa-apa.”
“Jadi… kita tetap dekat?” tanya Rafi.
Aira tersenyum kecil. “Tetap dekat. Dan kalau nanti ternyata kita berani lebih dari itu, ya kita lihat nanti.”
Rafi merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Masih ada ketakutan, masih ada keraguan, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih besar dari semuanya: harapan.
Aira menatapnya seperti membaca pikiran. “Kamu tahu nggak, Raf?”
"Apa?”
“Langit sore itu masih sama kok. Cuma… sekarang aku rasa kamu mulai berani datang.”
Rafi tertawa lirih. “Masih nyangkut sih. Tapi mungkin pelan-pelan turun.”
Aira tertawa juga. “Pelan-pelan aja. Yang penting kamu nggak hilang.”
Rafi mengangguk. “Aku nggak akan hilang.”
Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua benar-benar percaya pada kalimat itu.
Di atas mereka, langit malam membentang luas—tanpa senja, tanpa keraguan warnanya—hanya gelap penuh bintang yang seakan mengawasi dua hati muda yang sedang belajar berjalan di antara rasa takut dan keberanian.
Kadang, cinta tidak harus dimiliki sepenuhnya untuk terasa nyata.
Tapi malam itu, Rafi dan Aira mulai menemukan bahwa mungkin… cinta juga tidak harus selamanya ditahan.
Beberapa hari setelah percakapan di lapangan malam itu, kehidupan berjalan seperti biasa—atau setidaknya, terlihat biasa. Namun bagi Rafi, ada sesuatu yang berbeda. Cara Aira memandangnya, cara ia tersenyum, bahkan cara ia memanggil namanya, semuanya terasa punya makna baru. Tidak berlebihan, tidak meledak-ledak, tapi ada kehangatan yang dulu tidak pernah ia sadari.
Contohnya pagi itu, ketika Rafi baru masuk kelas dan menemukan selembar sticky note kuning di mejanya.
“Jangan lupa sarapan. Nanti pusing pas matematika. —A.”
Rafi tertawa sendirian. Catatannya sederhana sekali, tapi dadanya hangat seperti habis minum teh di pagi buta.
“Wih, senyum-senyum sendiri,” goda Dimas yang baru duduk.
“Apaan sih,” sahut Rafi sambil cepat-cepat menyembunyikan sticky note itu di buku tulisnya.
Pelajaran dimulai, tapi sepanjang jam matematika ia tidak benar-benar bisa fokus pada deret angka dan rumus yang tertulis di papan. Pikirannya melayang kembali pada Aira yang duduk tiga baris di depan. Sesekali Aira menoleh, dan setiap kali mata mereka bertemu, Rafi cepat-cepat pura-pura menulis sesuatu.
Waktu terasa bergerak lambat, seperti menunggu sesuatu terjadi.
Saat istirahat, Rafi sedang membeli air minum di kantin ketika seseorang menepuk bahunya. Ketika ia menoleh, ia sedikit terkejut. Kevin berdiri di belakangnya.
“Eh… Kev,” katanya canggung.
Kevin tersenyum ramah. “Santai aja, bro. Gue cuma mau ngomong bentar.”
Rafi mengangguk pelan. Mereka berjalan ke sisi kantin yang agak sepi. Kevin menyandarkan tangannya ke meja kosong.
“Aira bilang kalian sahabatan lama ya?” tanya Kevin.
“Iya,” jawab Rafi, berusaha tenang.
Kevin mengangguk beberapa kali, seolah sedang menyusun kata-kata. “Gue lihat cara lo liat dia waktu pertandingan kemarin.”
Wajah Rafi langsung panas. “Lo jangan salah paham. Gue—”
“Tenang,” potong Kevin. “Gue nggak mau ribut. Gue cuma mau bilang… Aira itu anak baik. Dan dia lagi banyak mikir.”
Rafi diam. Kevin menatapnya lebih serius.
“Kalau dia milih lo suatu hari nanti… jangan disakitin.”
Hening beberapa detik. Lalu Kevin tersenyum kecil dan menepuk bahu Rafi sebelum pergi begitu saja.
Rafi berdiri terpaku. Kata-kata sederhana itu terasa seperti angin kencang yang menerbangkan segala kekhawatiran yang selama ini memerangkap dirinya. Entah kenapa, ia merasa lega—sangat lega.
Sore harinya, setelah pulang sekolah, Aira mengajak Rafi ke ruang musik. Tempat itu jarang dipakai, kecuali oleh anak ekstrakurikuler band. Ruangannya tenang, bau kayu dan debu bercampur, tetapi nyaman.
“Aku mau tunjukin sesuatu,” kata Aira sambil membuka keyboard elektronik di sudut ruangan.
Rafi mengangkat alis. “Kamu bisa main?”
“Dikit-dikit,” jawab Aira. “Tapi ini bukan soal mainnya. Dengerin, ya.”
Ia menekan beberapa nada. Melodi sederhana, masih mentah, tapi lembut—seperti suara yang ingin mengatakan sesuatu tapi belum berani.
“Aku mikir lagu ini sejak beberapa hari lalu,” kata Aira. “Kayak… perasaan yang belum selesai.”
Rafi berdiri di sampingnya, mendengarkan dengan serius.
“Indah,” katanya jujur.
Aira tersenyum tipis. “Aku belum tau judulnya. Tapi kalau aku harus kasih judul sekarang…”
Ia berhenti bermain, lalu menatap Rafi.
“…mungkin aku bakal namain ‘Pelan-Pelan’. Soalnya… ya itu. Kita jalan pelan-pelan.”
Rafi merasa jantungnya seperti ikut mengetuk-ngetuk tuts keyboard. “Aira…”
Aira menunduk dan merapikan rambutnya yang terlepas dari kuncir. “Aku nggak mau buru-buru. Aku masih takut. Tapi aku juga nggak mau pura-pura nggak ada apa-apa. Jadi… kalau kamu mau, kita terus kayak gini aja dulu. Dekat. Jujur. Nggak perlu label apa-apa.”
Rafi mengangguk. “Aku mau.”
Aira tertawa kecil, lega. “Syukurlah. Aku kira kamu bakal kabur.”
“Gila aja aku kalo kabur,” balas Rafi.
Mereka tertawa bersamaan. Suara tawa mereka memantul di ruangan kecil itu—bahagia, ringan, dan sama sekali tidak dipaksakan.
Di luar jendela, langit sore mulai berubah warna. Bukan senja yang tajam, bukan malam yang pekat—hanya perpaduan lembut yang melukis langit dengan jingga muda.
Aira menatapnya sambil berkata, “Kayaknya langitnya cocok sama kita sekarang.”
Rafi menatapnya balik. “Langit yang nggak buru-buru datang atau pergi?”
Aira mengangguk. “Langit yang… siap kalau nanti warnanya berubah.”
Rafi tersenyum. “Kita juga bakal siap, ya?”
Aira mengulurkan tangannya. “Pelan-pelan.”
Rafi menggenggamnya. “Pelan-pelan.”
Dan untuk pertama kalinya, genggaman itu terasa seperti sebuah awal.